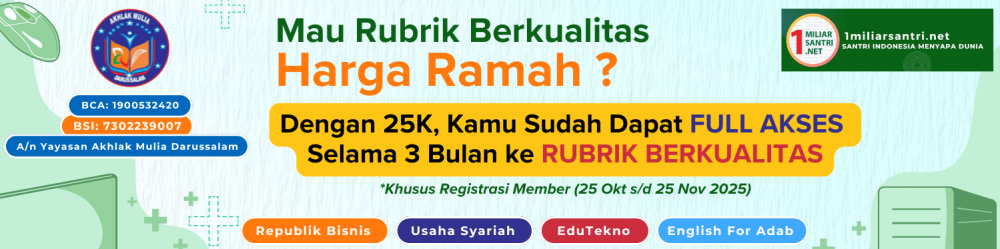Gresik — 1miliarsantri.net : Sebenarnya banyak ulama Bawean zaman dulu yang berperan dalam mensyiarkan agama Islam, baik di Bawean maupun di luar Bawean. Namun, hanya ada 13 ulama Bawean yang fotonya ditemukan dan berhasil ditelusuri jejak kehidupannya. Dalam sejarah Bawean sendiri telah terekam para ulama besar yang lahir di pulau kecil ini. Semua ini berkat penelitian yang dilakukan sejarawan Islam-Bawean, Burhanuddin Asnawi dan kita harus berterima kasih kepada. Dia adalah putra Bawean asli yang telah berhasil menulis biografi para ulama Bawean, termasuk yang berkiprah hingga ke Tanah Suci Makkah. Para ulama tersebut adalah sebagai berikut : Ulama Bawean generasi pertama ini muncul pada abad ke-19 M. Dia adalah seorang alim yang lahir di Pulau Bawean sekitar 1820-an. Ibunya berasal dari Bawean, sedangkan ayahnya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Asy’ari menghabiskan masa mudanya dengan belajar dari pesantren satu ke pesantren lainnya di Tanah Jawa. Setelah itu, jejak rihlah ilmiahnya bisa ditemukan sampai ke Maroko, sebelum akhirnya hijrah ke Makkah pada 1892 dan juga ke Mesir. Kiai Asy’ari dikenal sebagai maestro ahli falak dari Nusantara. Kiai Asya’ri wafat di Pasuruan pada 1921 M. Namun, ada juga yang mencatat tahun wafatnya pada 1918 M. Jenazahnya dimakamkan di daerah Sladi Kejayan Pasuruan, tepatnya di belakang Pondok Pesantren Besuk, di samping makam Wali Kemuning. KH Dhofir merupakan putera dari pasangan Kiai Habib dengan Hj Khadijah. Keluarga ini berasal dari Desa Patar Selamat atau Dissalam yang kemudian menetap di Dusun Bengko Sobung, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Bawean, Gresik. Kiai Dhofir lahir sekitar 1885-an atau pada penghujung abad ke-19. Pada periode ini, Islam di Bawean sedang memasuki fase keemasannya. Saat itu pula lahir generasi emas Bawean yang sulit dicarikan gantinya hingga sekarang. Kiai Dhofir dikenal sebagai ulama berdarah Bawean hafal Alquran. Dia wafat di Jakarta pada 19 Agustus 1971 dan dimakamkan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, setahun kemudian, jenazahnya diterbangkan dari Jakarta menuju Surabaya, lalu dimakamkan di komplek pemakaman Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Syekh Muhammad Zainuddin al-Baweani adalah salah seorang ulama bedar yang pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram, Makkah. Ulama beradarah Bawean ini kerap dipanggil Syekh Zein. Dia lahir di Makkah pada 1334 Hijriah atau 1915 Masehi. Ayahnya adalah Syekh Abdullah bin Muhammad Arsyad bin Ma’ruf bin Ahmad bin Abdul Latif al-Baweani. Penisbatan al-Baweani merupakan keterangan berharga yang tidak bisa dipisahkan dengan nama Syekh Zein. Syekh Zein mewarisi ilmu ulama Hijaz lintas generasi. Ia adalah generasi terbaik yang telah mengharumkan nama Nusantara sebagai seorang ulama yang berpengaruh di negeri Hijaz. Syekh Zein wafat di Makkah pada 1426 Hijriah atau 2005 Masehi. KH Abdul Hamid Thabri lahir di Desa Sidogedungbatu pada 20 September 1899 M. Dia adalah putera dari KH Thabri bin Nur bin Abdul Muthallib. Dari segi usia, Kiai Hamid lebih tua dari Syekh Zein. Tetapi, Syekh Zein lebih dahulu tiba di Makkah dan sejak kecil telah menetap di Tanah Suci. Periode Makkah menjadi catatan penting bagi perjalanan karir Kiai Hamid. Dia berada di Makkah untuk pertama kalinya pada 1921-19-25 dan berguru kepada Syekh Khalid bin Halil, seorang alim asal Makkah yang kelak hijrah ke Desa Tambak, Pulau Bawean. Selain mendirikan pesantren di Bawean, Kiai Hamid juga pernah menjadi komandan Hizbullah, sebuah badan kelaskaran dari barisan pemuda NU dalam perjuangan kemerdekaan. Kiai Hamid wafat di Dusun Pancor, Desa Sidogedungbatu pada 25 April 1981. Jenazahnya dimakamkan di komplek pesarean keluarga di Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor. KH Subhan bin Rawi juga termasuk seorang ulama Bawean yang pernah menuntut ilmu hingga ke Makkah. Kiai Subhan lahir di Dusun Iliran, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Bawean. Namun, tidak diketahui tanggal dan tahun kelahirannya. Nama kecilnya adalah Asrari. Pada 1927, untuk pertama kalinya dia bertolak dari Pulau Bawean menuju Tanah Suci Makkah. Dia berangkat ke Makkah mengikuti neneknya yang bernama Hj Ruqayyah binti Anwar. Pda 1957, Kiai Subhan kemudian pulang ke Pulau Bawean dan mulai merintis pengajian. Melalui pengajian tradisional, sarjana Hijaz ini terus mengabdikan hidupnya selama lebih dari 20 tahun. Penerusnya, KH Badrus Surur kemudian mendirikan Pondok Pesantren Darussalam Daun. Kiai Subhan tutup suia pada 1978. Ia menjadi salah seorang ulama penting yang mempengaruhi tradisi keagamaan di Desa Daun dan dikenal sebagai ulama yang pakar dalam bidng ilmu Faraidh. Nama Syekh Ahmad Hasbillah bin Muhammad atau Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad al-Maduri al-Habsyi ditemukan dalam silsilah tarekat Qadiriyah wan Nasqsyabandiyah. Dia adalah seorang ulama asal Makkah yang hijrah ke Nusantara dan kemudian tinggal untuk beberapa waktu di pulau Bawean. Karena itu lah dia dimasukkan sebagai ulama Bawean. Namun, dalam penelitiannya, Burhanuddin Asnawi belum berhasil mencatat tahun kelahirannya maupun tahun wafat Syekh Ahmad Hasbillah. Tahun kelahiran ulama Bawean yag satu ini juga tidak diketahui, begitu pun tahun wafatnya. Dari silsilahya, Syekh Khalid merupakan putra dari Syekh Khalil bin Khalifah. Ayahnya, Syekh Khalil kemudian menginjakkan kakinya di Pulau Bawean. Dia tinggal di Desa Tambak hingga tutup usia, sebelum kembali ke Makkah. Syekh Khalid tercatat memiliki hubungan dengan para ulama asal Pulau Bawean yang tinggal di Singapura. Karena itu, dia pun berkeinginan untuk mengunjungi Pulau Bawean. Dia juga ingin mengunjungi pusara sang ayah, Syekh Khalil yang terletak di Desa Tambak. Hingga pada akhirnya, takdir membawa Syekh Khalid ke Bawean dan menetap di Desa Tambak hingga akhir hayatnya. KH Abdul Hamid Satren juga merupakan seorang ulama keturunan Pulau Bawean. Dia adalah putra dari KH Ramli asal Desa Kebuntelukdalam, Kecamatan Sangkapura. KH Abdul Hamid kemudian menikahi seorang wanita asal Desa Diponggo, Kecamatan Tambak dan ikut tinggal bersama istrinya. Di Desa Diponggo, Kiai Abdul Hamid atau yang dikenal dengan Mas Doel, kemudian merintis pesantren. Akan tetapi, takdir berkata lain, ia harus hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di sebuah perkampungan bernama Satrean di Probolinggo, Jawa Timur. Karena itu lah dia dikenal sebagai Kiai Abdul Hamid Satrean. Mas Doel dikenal sebagai ulama alumni Hijaz yang aktif sebagai guru di Makkah. Namanya juga dikenang sebagai Rijal al-Makkah. Hingga akhir hayatnya, Mas Doel tidak dikaruniai anak. Dia dimakamkan di Satrean. Kiai Muhammad Amin bin Sawar merupakan tokoh kunci perkembangan kehidupan intelektual di Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Bawean, Gresik. Pada masanya, Kiai Amin pun menjadi ulama karismatik dan disegani oleh masyarakat Bawean. Dia dikenal tegas menjalankan fikih…