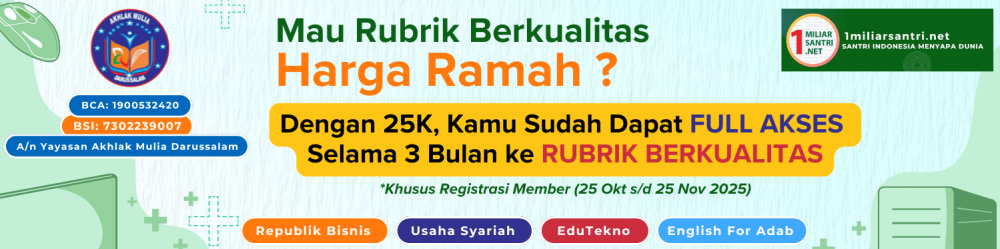Jakarta — 1miliarsantri.net : Perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari peran penting para Kiai dan Santri yang berada dilingkungan Pondok Pesantren. Perjuangan, pengabdian serta pengorbanan mereka pada saat itu sangat luar biasa, hingga mengalami berbagai macam ancaman dan sebagainya. Dari sekian banyak Pondok Pesantren di Indonesia, terdapat 10 Pondok Pesantren tertua dan tercatat dalam sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Berikut kami sajikan 10 Pondok Pesantren tertua di Indnesia yang telah di himpun tim redaksi 1miliarsantri.net : Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Sayid Abdur Rasyid bin Abdul Majid Al-Hasani dan ibunya bernama Syarifah Zulaikha binti Mahmud bin Abdullah bin Sayid Shahabuddin Al-Huseini seorang qodhil qudhoh di Inath. Ayah dari Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani merupakan keturunan Rasulullah Saw ke-22 dari Sayidina Hasan ra., melalui jalur Sayid Abdul Bar yang merupakan putera dari Sayid Abdul Qadir al-Jaelani al-Baghdadi. Sayid Abdul Kahfi Al-Hasani datang ke Jawa tahun 852 H/1448 M ketika masa pemerintahan Prabu Kertawijaya Majapahit atau yang dikenal dengan julukan Prabu Brawijaya I (1447 – 1451). Sayyid Sulaiman, yang merupakan keturunan Rasulullah SAW dari marga Basyaiban asal Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Sayyid Abdurrahman, seorang perantau dari Hadramaut, Yaman. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Khodijah, putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Kiai Syafii Pijoro Negoro merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribig, Jatinom, Klaten. Sebelum menetap di Kampung Dondong, Kiai Syafii menjadi salah satu Komandan Pasukan Sultan Agung yang ikut menyerbu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur di Batavia (Jakarta) pada 1629. Setelah peristiwa penyerbuan itu, Kiai Syafii singgah dan kemudian bermukim di Kampung Dondong. Pada mulanya, setelah menetap di Kampung Dondong, Kiai Syafii mendirikan padepokan. Namun, yang datang untuk belajar justru santri, yang hendak belajar ilmu agama. Maka, padepokan itu pun bertransformasi menjadi pesantren ditandai dengan dibangunnya musala yang kini dikenal sebagai Musala Abu Darda’. Hingga kini musala itu masih berdiri kukuh setelah mengalami beberapa kali renovasi. Adalah Kiai Abdul ‘Allam perintis pendirian pondok pesantren yang berada di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ini. Sejarah perjuangan Kiai Abdul ‘Allam hingga merintis pendirian pesantren Nazhatut Thullab terekam dalam Babad Ranah Pajjan. Ia yang membuka daerah yang kini dikenal sebagai Desa Prajjan itu. Konon, Kiai Abdul ‘Allam memiliki nama asli Pang Ratoh Bumi. Ia berasal dari Sumenep, kota yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Kiai Abdul ‘Allam adalah nama pemberian dari Hadratus Al Syaikh Aji Gunung Sampang, gurunya mengaji. Saat berguru pada Syaikh Aji Gunung, atau dikenal juga dengan julukan Buju’ Aji Gunung, Kiai Abdul ‘Allam memiliki dua sahabat karib dari Jawa yang memperoleh julukan Buju’ Napo dan Gung Rabah Pamekasan. Kedua sahabat ini ikut mewarnai perjalanan hidup Abdul ‘Allam. Berdasarkan hikayat yang berkembang di masyarakat, Kiai Abdul ‘Allam termasuk salah seorang yang intens melakukan komunikasi dengan Pangeran Cakra Ningrat II ketika sang pangeran ini ditangkap dan diasingkan oleh Penjajah Belanda ke Madura. Peristiwa itu terjadi pada periode 1674-1679. Pada saat itu, Kiai Abdul ‘Allam dan Pangeran Cakra Ningrat II sering membahas perjuangan rakyat melawan Belanda. Karena itu, berdasarkan hikayat ini, Kiai Abdul ‘Allam menjadi salah satu tokoh perlawanan terhadap Belanda bersama Pangaran Cakra Ningkrat II. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Syekh Hasanuddin merupakan seorang pengembara yang selalu menyebarkan Islam di wilayah yang disinggahinya. Tidak terkecuali di pedukuhan Babakan. Di wilayah ini, syekh Hasanuddin membuat mushola kecil yang digunakan untuk mengajarkan tentang agama Islam. Julukan Ki Jatira sendiri disematkan oleh murid-murid Syekh Hasanuddin, karena kebiasan Syekh Hasanuddin yang beristirahat dibawah dua pohon jati ketika sedang membangun mushola. Julukan jatira sendiri mengandung arti Jati = pohon jati, ra=loro (dua). Dipilihnya wilayah Babakan untuk dikembangkan menjadi wilayah pesantren, dikarenakan sosok Ki Jatira yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Kondisi Babakan yang memiliki lahan yang cukup kering dan sulit untuk dikembangkan dalam sektor pertaniannya, membuat Ki Jatira tertantang untuk mengembangkan wilayah tersebut sebagai pusat pendidikan Islam dan menjaga masyarakat untuk lepas dari pengaruh kekuasaan belanda. Tempat yang pertama kali dijadikan sebagai pondok pesantren Buntet, letaknya di Desa Bulak kurang lebih 1/2 km dari perkampungan Pesantren yang sekarang. Sebagai buktinya di Desa Bulak tersebut terdapat peninggalan Mbah Muqoyyim berupa makan santri yang sampai sekarang masih utuh. Salah satu sifat beliau adalah tidak mau koopratif dengan Belanda, yang banyak mencampuri urusan internal keraton, sehingga beliau lebih memilih tinggal di luar keraton dan mendirikan pesantren. Dalam perantuan inilah beliau memulai kehidupan sebagai kyai dengan mendirikan masjid dan gubuk kecil dan mulai mengajar agama. Dalam sejarahnya, pondok ini melewati dua periode, setelah mengalami kevakuman hampir 50 tahun, antara 1830 – 1878. Vakumnya pondok pada 1830 disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada 1825 di Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan serangkaian tipu muslihat dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro. Karena itu pada 1830, para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro di Surakarta dan Pakubuwono IV bersembunyi dan keluar dari Surakarta ke daerah lain, termasuk Kiai Jamsari II (putra Kiai Jamsari) dan santrinya. Setelah sekitar 50 tahun kosong, seorang kiai alim dari Klaten yang merupakan keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, Kiai H Idris membangun kembali surau tersebut. Tentunya lebih lengkap dan diperluas dari kondisi semula. Di tangan Kiai Idris inilah, Jamsaren mencapai puncaknya. KH. Hasan Munadi wafat pada usia 125 tahun. Beliau mengasuh pondok pesantren ini selama hampir 90 tahun. Beliau meninggalkan empat orang putra yaitu: KH. Isma’il, KH. Muhyini, KH. Ma’sum dan Nyai Mujannah. Pada masa itu, Pondok Gading belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pendirian pondok pesantren ini tidak lepas dari sosok santri Kyai Qomaruddin, yakni Raden Tumenggung Tirtorejo Bupati Kanoman Gresik. Saat itu Raden Tumenggung Tirtorejo mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam di pesisir utara Gresik. Kyai Qomaruddin, yang sebelumnya sudah mendirikan pesantren di Kanugrahan Lamongan, akhirnya pindah ke wilayah Kabupaten Gresik. Kyai Itsbat bin Ishaq merupakan seorang kyai yang berasal dari Sumber Panjalin. Jika ditelusuri, genealogi Kyai Itsbat bin Kyai Ishaq merupakan keturunan dari Kyai Cendana alias Sayyid Zainal Abidin, Kwanyar, Bangkalan dan masih keturunan Sunan Kudus. Demikian 10 Pondok Pesantren tertua yang dihimpun tim redaksi…