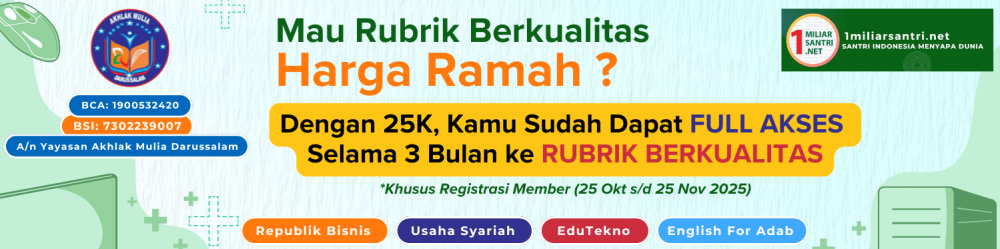Masjid Agung Lamongan, Selain Sebagai Masjid Tertua, Juga Sebagai Destinasi Wisata Religi
Lamongan — 1miliarsantri.net : Masjid Agung Lamongan merupakan salah satu masjid yang berkaitan erat dengan sejarah dan diklaim sebagai yang tertua di Lamongan. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1908 dengan gaya arsitektur Jawa yang khas, ternyata menyimpan Candra Sengkala berdirinya Kabupaten Lamongan. Lokasi Masjid Agung Lamongan (MAL) ini memang berada di pusat kota di mana pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari tata ruang kota di masa lalu, di mana alun-alun sebagai pusatnya dan berada di sebelah barat alun-alun kota Lamongan. Saat ini, Masjid Agung sudah dipugar menjadi lebih modern dengan ciri khas menara kembar. “Masjid Agung Lamongan ini didirikan pertama kali pada tahun 1908. Pada saat itu masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur Jawa, yaitu beratap tumpang 3 yang mengandung arti iman, islam dan iksan,” kata Sekretaris Takmir Masjid Agung Lamongan HM Yunani CH saat berbincang dengan 1miliarsantri.net, Senin (16/10/2023). Yunani menambahkan, tinggi 2 menara kembar di depan masjid agung Lamongan yang 53 meter, dibangun pada tahun 2012 dan ketinggian menara tersebut disesuaikan dengan usia Nabi Muhammad SAW saat hijrah. Beberapa kali renovasi dilakukan terhadap masjid ini sejak awal didirikan hingga ke bentuknya yang sekarang, namun tetap mempertahankan sejumlah benda yang adalaha objek cagar budaya, yaitu dua buah gentong, dua buah batu pasujudan (Prasasti) yang berada di depan masjid. “Dua gentong air dan 2 batu pasujudan tersebut masih ada di depan masjid dan konon katanya gentong dan batu pasujudan tersebut berkaitan erat dengan kisah Panji Laras dan Panji Liris dengan Andansari dan Andanwangi, Wallahu alam,” ujar Yunani. Masuk ke dalam masjid, kita akan melihat di tengah-tengah bangunan masjid ini masih mempertahankan bangunan asli atau bangunan awal ketika masjid ini didirikan, yaitu tiang besar penyangga masjid yang terbuat dari kayu jati. Menara awal yang dibangun pada sekitar tahun 1970-an juga masih tetap dipertahankan. Lokasi tempat mengumandangkan azan yang berada di loteng atau ketinggian juga masih ada meski sudah tidak digunakan kembali. “Ada beberapa kali pengembangan dengan tetap mempertahankan nilai awal hingga ke bentuk seperti yang ada saat ini,” paparnya. Di dalam masjid ini juga terdapat mushaf Al-Qur’an terbesar yang berada di sisi kanan masjid. mushaf Al-Qur’an ini memiliki ukuran 240 x 155 sentimeter buah karya dari Ustaz Rusdi Aliuddin, pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Iman, Desa Sidorejo, Kecamatan Deket. Mushaf Al-Qur’an yang memiliki ketebalan 17 cm itu memiliki berat sekitar 350 kg dan untuk melindunginya, mushaf Al-Qur’an raksasa itu disimpan dalam kotak kaca. “Setiap hari mushaf Alquran besar itu selalu dibaca,” imbuhnya. Masjid Agung Lamongan yang berada di jantung kota Lamongan ini menjadi satu dari sekian masjid di Lamongan yang kerap menjadi pilihan wisata religi di Lamongan. Lokasinya yang strategis dan keindahan arsitekturnya membuat kita kerasan untuk berlama-lama di masjid ini. Di samping itu kini masjid agung terus berbenah. Kalau dulunya pusat masjid berada di empat tiang itu, kini diperluas ke barat masjid dengan pembangunan mimbar masjid serta teras masjid. Masjid Agung Lamongan didirikan pada 1908 di atas tanah wakaf milik Mbah Yai Mahmoed. Ketika itu Lamongan dipimpin oleh seorang Adipati yang bernama Djojodinegoro.Berdasarkan catatan sejarahnya, Masjid Agung Lamongan didirikan tahun 1908 didirikan oleh Mbah Yai Mahmoed yang mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid pada masa Lamongan dipimpin seorang adipati bernama Djojodinegoro. “Ini adalah masjid tertua di Lamongan, didirikan pertama 1908 dengan status wakaf dari ulama mbahyai Mahmud, yang menurut sejarah adalah orang asli Bojonegoro, yang kemudian oleh Mbahyai Mahmoed diserahkan untuk dikelola ke KH Mastur Asnawi usai mukim selama 20 tahun mukim di Mekah,” lanjut Yunani. Setelah dikelola oleh Mbah Yai Mastur, ungkap Yunani, Mbah Yai Mastur mengajak bersama para kiai, ulama dan tokoh masyarakat di Lamongan untuk gotong royong membangun masjid tersebut. Cikal bakal masjid yang menggunakan empat buah kayu jati yang dipergunakan sebagai soko guru masjid itu didatangkan dari berbagai daerah. Tiga buah kayu jati di antaranya didatangkan dari Asembagus, Situbondo dan 1 lagi berasal dari Demak, Jawa Tengah. “Kayu jati tersebut diangkut dengan cikar atau pedati dan sudah disambut dengan meriah begitu tiba di perbatasan kota,” kisah Yunani. Lebih jauh, Yunani mengungkapkan, peran masjid agung Lamongan bagi perkembangan Lamongan, khususnya umat Islam juga tidak bisa dianggap kecil. Pasalnya, tambah Yunani, Candra Sengkala berdirinya Kabupaten Lamongan diduga ada di Masjid Agung Lamongan ini, yaitu ‘masjid ambuko sucining manembah’ seperti yang pernah ditulis oleh Tim Penggali Sejarah Hari Jadi Lamongan. “Saat ini sudah dilakukan perluasan tanah masjid di sebelah selatan hingga Jalan Basuki Rahmad serta dibuatkan pintu gerbang sebelah selatan itu,” imbuhnya. Tidak banyak yang tahu pula, di dalam masjid ini ada 4 nisan makam yang merupakan makam aulia yang berada di sisi utara masjid. Empat nisan tersebut adalah nisan Kiai Mahmoed, nisan kosong yang rencananya untuk istri Kiai Mahmoed yang hingga kini belum diketahui, nisan Kiai Mastoer Asnawi dan nisan yang berisi peralatan pertukangan milik dari Mbah Yai Mahmoed. “Kompleks makam yang aslinya ini dulu berada di luar ruangan, saat ini menjadi di dalam ruangan masjid Agung, termasuk menara masjid lama yang bangunannya menyerupai menara Madinah juga menjadi berada di dalam masjid,” paparnya. Kepala Disparbud Lamongan Siti Rubikah membenarkan jika di areal Masjid Agung Lamongan ada sejumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan sudah tercatat dalam SK Bupati Lamongan tentang benda cagar budaya dan juga dalam data BPCB. Benda cagar budaya yang berada di masjid dengan kapasitas 5600 jemaah tersebut, rinci Rubikah, di antaranya adalah Gentong air yang terbuat dari batu. “Dan 2 buah alas yang terbuat dari batu atau biasa disebut batu pasujudan yang kini telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya,” kata Siti Rubikah. Berada di pusat kota Lamongan, tepatnya di barat Alun-alun Lamongan di Jalan K.H Hasyim Asyari, Masjid Agung Lamongan menyimpan Mushaf Al-Qur’an berbahan kertas terbesar di dunia. Yunani CN mengungkapkan Al-Qur’an raksasa berbahan kertas ini memiliki ukuran 2,4 meter x 1,5 meter dengan ketebalan kertas 17 cm. Al-Qur’an ini, menurut Yunani, adalah karya KH. Rusdi Aliuddin, pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Iman, Desa Sidorejo, Kecamatan Deket. “Mushaf Alquran ini dikerjakan selama kurang lebih 2 tahun,” papar Yunani. Yunani merinci ukuran huruf yang ada pada Al-Qur’an memiliki tinggi sekitar 7 cm dan dibuat dengan kertas canson 300 gram yang diimpor dari Perancis dengan berat 350 kilogram. Tiga puluh…