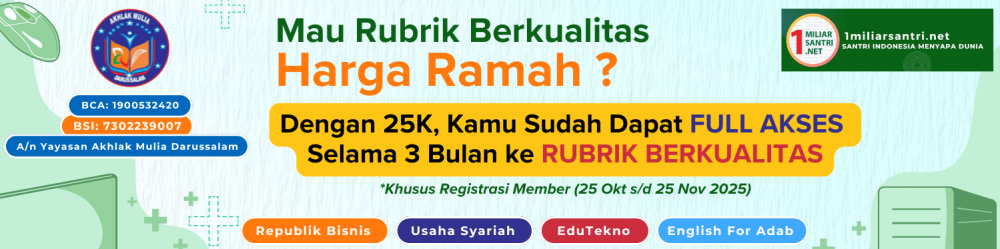Pekalongan — 1miliarsantri.net : Sosok ulama asal Kabupaten Pekalongan yang dikenal sakti pada zaman dahulu yakni Mohammad Arshal atau Wali Gendhon. Ulama yang lebih dikenal sebagai Mbah Gendhon tersebut dikenal sakti karena tirakatnya yang luar biasa. Ahli waris Makam Mbah Gendhon, M Arifin, menceritakan, kehidupan Mbah Gendhon sekitar tahun 1868-1960 Masehi. Mbah Gendhon merupakan anak pasangan Tarab dan Takumi. “Beliau (Mbah Gendhon) lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Mbah Gendhon merupakan anak satu-satunya,” katanya. Menurutnya, sejak kecil Mohammad Arshal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendhon dengan cara sederhana dan mandiri. “Sehari-hari menggembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasapun sifatnya tidak berubah. Bahkan malah semakin menjauhi duniawi,” terangnya. Sampai pada akhirnya, lanjut dia, kedua orang tua Mohmmad Arshal mengenalkannya kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya, setelah menikah Mohammad Arshal bersama rombongan pengantar malah kembali ke rumah orang tuanya. “Ternyata beliau (Mbah Gendhon) belum memiliki keinginan untuk berumah tangga. Namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok,” ungkapnya. Sehingga, Mbah Gendhon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya kedua orang tuanya merestui kepergiannya dengan memberikan bekal dan sedikit uang. “Mbah Gendhon mondok di Kyai Munir. Selama di pondok, sifatnya juga tidak berubah. Hal itu juga membuat sejumlah teman tidak menyukainya,” terangnya. Sekitar lima tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal. Sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. “Namun Mohammad Arshal hanya ditepian saja. Sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Namun setelah tercebur ke dalam sendang, beliau tak muncul kembali. Teman-temannya sudah mencari, bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Mohammad Arshal tidak ditemukan,” jelasnya. Sehingga, hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke Desa Kesesi, untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarga Mbah Gendhon. Kedua orang tuanya tetap tawakal dan sabar mendapat kabar tersebut dan berharap masih hidup. “Namun hingga puluhan tahun tak ada kabar keberadaan Mohammad Arshal tersebut. Sampai suatu saat musim kemarau tiba, tanaman kering dan mati semua. Bisa dikatakan saat itu paceklik,” ungkapnya. Tiba-tiba, lanjut dia, saat malam saat sunyi muncul angin kencang menerbangkan semua yang dilewatinya. Kedatangan angin disertai kilat dan suara keras petir. Sehingga tidak ada warga yang berani keluar rumah. “Kemudian rumah kedua orang tuanya tiba-tiba terdengar suara diketuk-ketuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, ayahnya membukakan pintu,” paparnya. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia. Sebab, anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. “Namun saat pulan itu pakaian beliau (Mbah Gendhon) tak lazim, yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang,” terangnya. Selama menghilang, Mbah Gendhon tinggal di hutan dan goa ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai cina dan bunga pohon jati. “Selama perjalanan, dia ditemani seorang harimau dan ular yang membantunya menyeberangi sungai,” katanya. Kedatangan Mohammad Arshal itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, Mbah Gendhon malah naik ke pohon kelapa. “Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap tidak bersedia turun. Hingga sekitar setahun kemudian turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itupun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan lagi. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya. Hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh,” ungkapnya. Kabar kepulangan Mohammad Arshal itu akhirnya sampai ke pengurus ponpes tempat dia menuntut ilmu agama. Sehingga pengurus ponpes beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arshal. “Saat tiba di Kesesi, para pengurus pondok tersebut lantas melakukan pertemuan khusus dan akhirnya pengasuh ponpes mengatakan logat Cirebon ‘Cung kiye Mohammad Arshal wes balik, sira susah pikir, bingung pikir sowan nang Moh. Arshal julukane Wali Gendhon’. Baru setelah ada kunjungan dari ponpesnya belajar dulu, Mbah Gendhon bersedia masuk kembali ke rumah,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, Mohammad Arshal juga memiliki peranan dalam kemerdekaan RI. Sebab, saat penjajahan Belanda, Mbah Gendhon juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. “Saat itu, rumah Mbah Gendhon digunakan untuk persembunyian para pejuang saat melawan Belanda. Mengetahui hal itu, Belanda lantas mengepung rumah beliau dan memborbardinya. Namun hanya menggunakan perisai berupa tampah, dengan izin Allah, rumah dan lingkungannya selamat dari serangan itu,” terangnya. “Pernah juga ditantang untuk membuktikan kewaliannya, dengan ditembak. Jika benar beliau wali Allah, maka tidak akan terluka jika ditembak. Saat senapan kompeni meletus, secepat kilat Mbah Gendon tak terlihat. Baru setelah kepulan asap senapan itu menipis, Mbah Gendhon memperlihatkan telah menangkap peluru itu,” jelasnya. Bahkan, lanjut dia, Mbah Gendhon juga memiliki peran mengusir Belanda dari lingkungannya. Mbah Gendhon hanya mengelilingi markas Belanda, para pasukan kompeni secara tiba-tiba tewas tanpa sebab. “Akhirnya markas itu bubar dan ditutup. Sejumlah kejadian itu, membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya bahwa Mbah Gendhon memiliki kelebihan karomah dari Allah SWT,” terangnya. Menurut M Arifin, ketenaran Mbah Gendhon tidak hanya sekitar Pekalongan saja. Namun hampir seluruh Nusantara sudah mengenal sosok Mbah Gendhon tersebut. “Saat itu sekitar tahun 1990-an, warga Malaysia itu berkunjung ke makam Mbah Gendhon didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu Mbah Gendhon dan diajar mengaji. Setelah itu, Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di Kesesi ini (makamnya) kepada warga Malaysia itu. Ya kaget saat tiba di sini, karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendhon sudah meninggal sekitar tahun 1960’an,” paparnya. Warga Lampung juga hampir sama ceritanya. Namanya Pak Sodikin kalau tidak salah. Dia ke sini sekitar tahun 2000’an. “Dia cerita kalau tiga bulan sebelumnya bertemu Mbah Gendhon di hutan, ngobrol-ngobrol dan kemudian dikasih alamat di Kesesi ini. Kaget juga setelah sampai sini, karena ternyata Mbah Gendhon sudah meninggal,” tambahnya. Diungkapkan, setiap tahun selalu diadakan khaul Mbah Gendhon tersebut. Khaul tersebut biasanya diadakan setiap Ahad Legi Jumadil Awal. “Setiap khaul biasanya jamaahnya sampai puluhan ribu. Penuh semua sini. Makam yang pertama kami pindah karena tergerus air sungai. Jaraknya tidak jauh dari makam yang sekarang. Lokasi yang sekarang ini juga atas permintaan beliau (Mbah Gendon). Sebab…