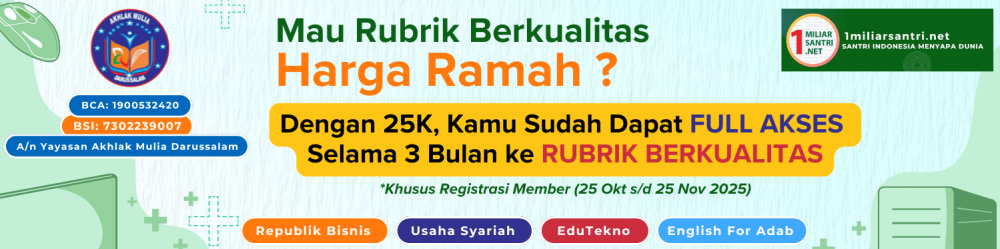Banyak Warman Jadi Raja di Indonesia Dulu
Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Beberapa toh jaman kerajaan dahulu terdapat nama Warman dan menjadi raja di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Hanya Warman di Sriwijaya yang tidak terkenal. Di Melayupura ada Adityawarman yang terkenal. Namanya sempat diusulkan oleh Muh Yamin sebagai nama universitas di Padang, tetapi kalah dengan nama Andalas. Di Kutai ada Mulawarman yang sangat terkenal, namanya diabadikan menjadi Universitas Mulawarman di Samarinda. Di Tarumanegara ada Purnawarman yang terkenal, tetapi namanya hanya diabadikan sebagai nama jalan di Bandung. Justru Adityawarman yang pernah dipakai sebagai nama institute, yaitu Institit Teknologi Adityawarman, sekarang menjadi Universitas Kebangsaan. DI Sriwijaya, raya yang terkenal adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai pendiri Sriwijaya, Samaratungga (abad ke-8), dan Balaputradewa (abad ke-9). Sosok Warman ada menjadi raja Sriwijaya kedua pada awal abad ke-8) yaitu Indrawarman, tetapi tidak masyhur. Setelah Balaputradewa ada lagi raja bernama Warman, yaitu Sri Udayadityawarman (abad ke-10). Kemudian Sri Marawijayatunggawarman (awal abad ke-11), dan Sri Sanggrama Wijayatunggawarman (abad ke-11). Marawijayatunggawarman dikenal hanya melanjutkan kebesaran yang dicapai sebelum-sebelumnya. Sedangkan Sri Sanggrama Wijayatunggawarman dikenal karena pada masanyalah Sriwijaya mengalami kemunduran. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur memiliki 20 raja. Tetapi hanya 12 raja yang bernama Warman. Pendiri Kutai namanya Kudungga, disebut oleh Paul Michel Munoz di buku Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia bukan berasal dari Hindustan. Oleh anaknya, Aswawarman, Kudungga diberi nama Warman juga. Sehingga ada 13 Warman yang menjadi raja Kutai. Kudungga sebagai pendiri Kutai, yang kemudian diberi nama Dewawarman, digantikan oleh Aswawarman. Mulawarman yang menggantikan Aswawarman menjadi raja Kutai yang paling terkenal, karena di masa Mulawarmanlah Kutai mencapai masa kejayaan. Setelah Mulawarman, berturut-turut ada Marawijayawarman, Gajayanawarman, Tunggawarman, Jayanagawarman, Nalasingawarman, Gadinggawarman Dewa, Indrawarman Dewa, Sanggawarman Dewa, dan Candrawarman. Raja ke-13 dan ke-14 bukan Warman. Raja ke-15 bernama warman lagi, yaitu Wijayawarman. Raja ke-16 hingga ke-20 bukan Warman lagi. Di Tarumanegara ada 12 raja, semua bernama Warman. Raja pertama bernama Jayasingawarman, lalu diganti oleh Dharmayawarman, dan kemudian Purnawarman, raja ketiga yang paling terkenal. Setelah Purnawarman ada Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudhawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan terakhir: Linggawarman. Di antara mereka ada yang memiliki nama yang sama dengan raja Kutai. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara berhasil memiliki ibu kota pemerintahan yang disebut Sundapura. Purnawarman adalah raja ketiga Tarumanegara yang bernama Warman. Pada masa Purnawarman pula digali sungai sepanjang 12 kilometer untuk melancarkan perdagangan dengan kerajan-kerajaan lain. Prasastr-prasasti peninggalan Tarumanegara menjadi catatan sejarah tentang Indonesia zaman dulu. Di Melayupura, Adityawarman menjadi raja yang terkenal. Dua raja sebelum dia tidak menggunakan nama Warman. Tetapi raja ketiga yang kemudian digantikan oleh Adityawarman bernama Akarendrawarman. Anak Adityawarman, Ananggawarman mengagntikannya, lalu memindahkan ibu kota Kerajaan Melayupura ke Pagaruyung. Ia digantikan oleh Wijayawarman. Setelah Wijayawarman, kerajaan sepenuhnya menganut tradisi Islam, dan raja menggunakan gelar sultan. Menurut Paul Michel Munoz, warman atau varman berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya pelindung. Asal mula kata menunjukkan bahwa mereka berasal dari India. Bermigrasi ke Nusantara lalu menjadi raja. Migrasi orang India ke Nusantara dilakukan oleh kaum Saka, yang namanya diabadikan sebagai nama tahun Saka. Mereka datang baik sebagai biarawan maupun sebagai pedagang. Ada pula bangsawan. (jeha) Baca juga :