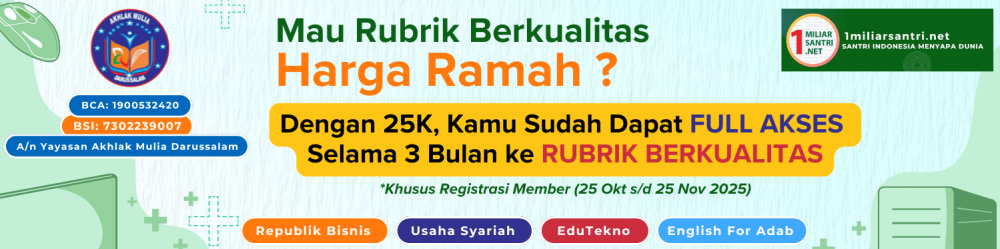KH Zuhdi Takeran : Kejadian Penculikan Para Kiai Selalu Kami Ingat Hingga Akhir Hayat
Magetan – 1miliarsantri.net : Rekam jejak kejahatan dan kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat dirasakan bagi seluruh penghuni Pondok Pesantren Takeran Magetan, bukan hanya santri, pengasuh dan pengurus tapi juga seluruh jamaah sangat teringat betul ketika terjadi nya peristiwa penculikan Kiai Imam Mursyid Muttaqirn pada 18 September 1948. KH. MS Zuhdi Tafsir, S.Ag atau akrab disapa Mbah Zuhdi, pendiri sekaligus Pengasuh Ponpes Cokrokertopati, dan juga generasi penerus Pesantren Takeran Magetan, secara ekslusif menuturkan kisah pilu tersebut kepada 1miliarsantri.net. Habis shalat Jumat, saya bersama para santri pondok yang sedang duduk-duduk di serambi masjid melihat ada mobil datang ke pesantren. Mobil itu warnanya hitam dan bentuknya kecil. Bersama mereka terlihat beberapa orang membawa stand gun dan ada yang membawa karaben. Di situ saya lihat ikut datang seseorang yang katanya berasal dari Jombang sebagai pemimpin rombongan. Orang itu beberapa waktu kemudian saya tahu namanya Suhud. Sesampai di pesantren dan bertemu Kiai Imam Mursyid Mutaqin, ia kemudian berkata dengan mengutip ayat Alquran yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum (bangsa) kecuali mereka yang berusaha mengubah nasibnya sendiri. Jadi, katanya rombongan yang datang itu ingin mengubah nasib bangsa Indonesia. Tapi, sebelum mereka datang di sekitar pesantren sudah tersebar pamflet yang isinya: Muso, Moskow, Madiun. Pamflet itu tersebar di sepanjang jalan raya yang ada di depan pesantren. Saya yang saat itu duduk di bangku kelas 1 SMP ikut membaca pamflet itu. Nah, rombongan yang dipimpin Suhud yang di situ ada pejabat camat Takeran yang menjadi anggota PKI itulah yang menculik Kiai Mursid. Saat itu juga Kiai dibawa pergi. Jadi, Anda masih ingat peristiwa itu? Iya betul, bahkan sampai kini mimik wajah, warna pakaian para penculik itu semuanya saya masih ingat. Yang membawa pergi adalah seseorang yang memakai piyama warna krem. Dia pergi bersama Kiai Mursyid yang diapit oleh Suhud dan camat Takeran yang jadi anggota PKI itu. Setelah Kiai Mursyid dibawa pergi, kompleks pesantren ini saat itu kemudian di-stealing (dikepung) oleh para anggota PKI lainnya. Kami dikepung selama sekitar seminggu. Kami ingat betul pengepungan itu membuat persediaan garam di pesantren habis. Kami dikepung sekitar tujuh hari hingga pasukan Siliwangi datang membebaskan kami. Kemudian bagaimana nasib Kiai Mursyid? Semenjak dibawa pergi itulah, kami sampai kini tidak mengetahui dimana keberadaan Kiai Mursyid. Namun, seorang pemuda yang masih menjadi kerabat dan tinggal tak jauh dari pesantren melaporkan bila beberapa hari sebelum penculikan itu, desa-desa di sekitar Takeran dikepung oleh orang-orang yang berseragam hitam-hitam. Mereka juga mengepung kantor Kecamatan Takeran. Beberapa rumah haji juga di sekitar Takeran didatangi, didobrak pintunya, dan penghuninya diancam. Mereka juga memukulinya dan memaksa agar tunduk pada PKI. Kata mereka: Kamu mau tunduk tidak? Kalau tidak, terus dipukuli. Dan, baru berhenti setelah menyatakan menerimanya. Di situlah saya lihat, penculikan itu memang disengaja dan sistematis. Para kader PKI terlihat sudah betul-betul siap melaksanakan gerakannya. Mereka bergerak ke mana-mana. Apakah ada korban lain selain Pak Kiai Mursyid? Yang diculik langsung di depan santri memang hanya beliau. Tapi, beberapa hari kemudian banyak santri dan pengurus pesantren juga hilang diculik mereka. Yang hilang itu kerabat kami Moh Suhud (Ayah Mantan Ketua MPR/DPR Moh Kharis Suhud) seorang guru yang mengajar di Mualimin milik pesantren Takeran, kakak ibu saya Imam Faham, ada Ustaz Hadi Addaba’ (orang Arab yang menjadi guru bahasa Arab) di Pesantren Takeran, Maijo (Kepala MI Takeran). Ada juga yang ikut hilang, yakni Husen (anggota Hizbullah). Juga ada beberapa keluarga kiai pengikut tarekat yang ikut dibunuh. Nama-nama mereka sudah saya lupa persisnya. Namun, sekitar tahun 1964 setelah jasad nya diangkat dari sumur, jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Madiun dan Magetan. Menurut Anda, apa yang membuat pengikut PKI itu begitu membenci para kiai dan santri sehingga mereka tega membunuhnya? Saat kejadian saya tak tahu mengapa itu terjadi. Namun, ketika saya mulai besar dan kuliah, saya mulai paham apa dan mengapa peristiwa pembantaian PKI di Madiun terjadi. Apalagi, pesantren kami ini semenjak dahulu adalah basis pergerakan. Leluhur kami adalah seorang pangeran dari Yogyakarta (Pangeran Kertopati) yang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Dan, di pesantren ini pula Masyumi itu digagas. Jadi, lingkungan kami adalah orang yang paham dunia pergerakan. Nah, setelah lepas dari situasi itu, dan ketika saya mulai kuliah saya makin paham dengan situasi politik. Mulai tahun 1960-an, agitasi politik dari PKI memang terus menaik tinggi. Dan, sama dengan tahun 1948, agitasi itu juga mulai menargetkan dan menyerang posisi kiai yang katanya jadi bagian tujuh setan desa karena punya tanah luas. Kalau begitu, peristiwa 1948 terus terbawa-bawa hingga 1965? Peristiwa penculikan di September 1948, di mana anggota PKI menipu kami dengan mengajak Kiai Mursyid berunding dan kemudian menculik dan membunuhnya, itu berbekas di hati. Ketika semakin besar, saya kemudian mencari jawabannya, misalnya dengan memperlajari sejarah revolusi kaum buruh di Rusia atau revolusi Cina yang dipimpin Mao Zedong. Di situlah, saya tahu Muso itu muridnya Lenin yang lari ke Moskow setelah memecah Syarikat Islam. Dan dari situ pula, saya yakin bila partai komunis itu partai yang bersenjata yang siap merebut kekuasaan kapan saja ketika waktunya tiba. Di desa-desa sekitar Takeran, semenjak perayaan ulang tahun PKI tahun 1964, terdengar seruan bagi-bagi tanah. Sebutan setan desa muncul di mana-mana. Saat itulah, kami yakin peristiwa seperti 1948 akan terjadi lagi dan bisa dipastikan akan terjadi kapan saja. Maka untuk mengenang para korban kebiadaban, kejahatan dan kebengisan PKI, setiap tanggal 30 September, kami selalu mengadakan acara Doa bersama, pemutaran film G-30 S/PKI dan tentunya ziarah ke makam pahlawan serta dibeberapa tempat yang dijadikan pembantaian PKI. (fq)