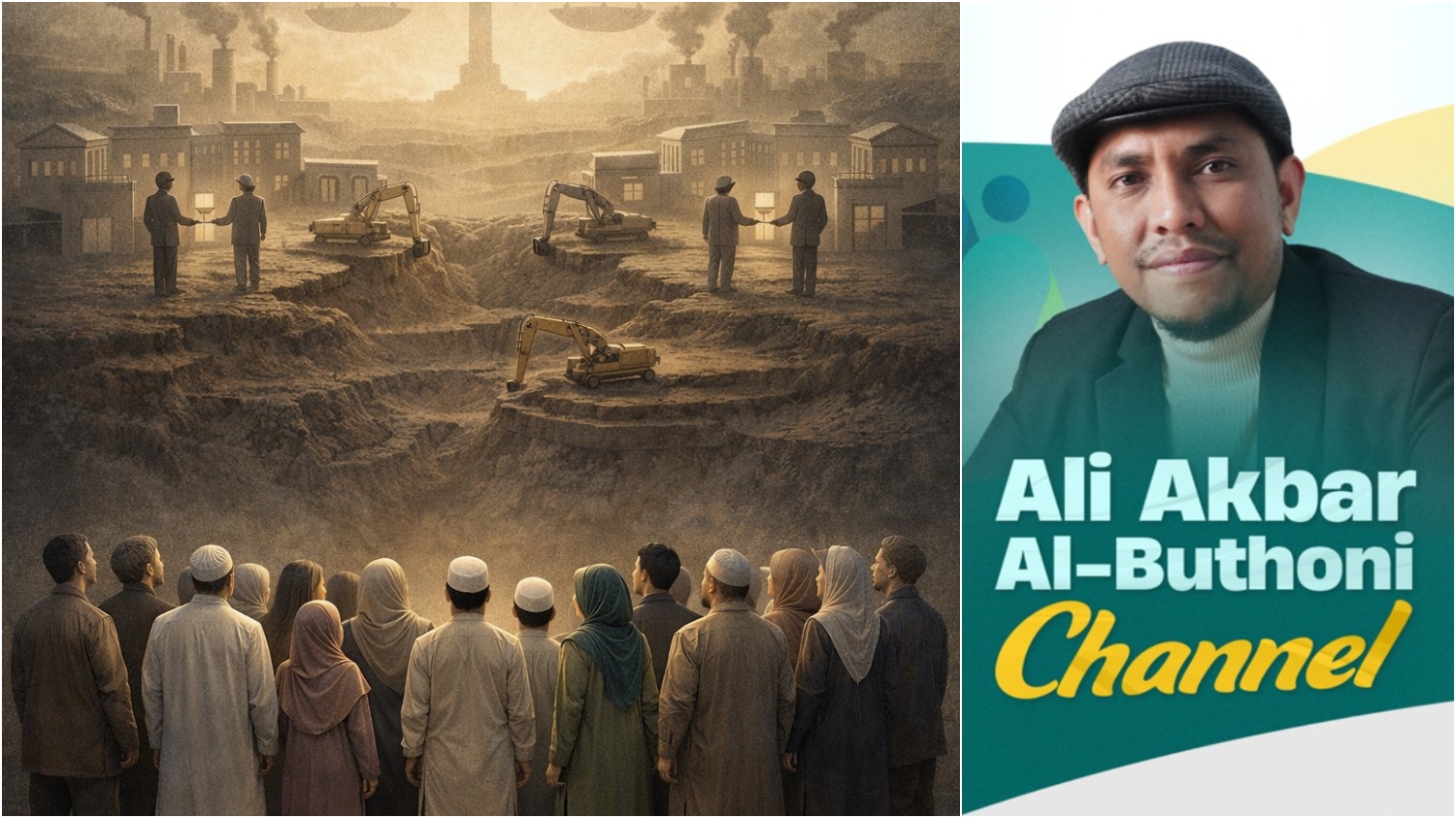Tragedi Kemanusiaan Jurnalis di Gaza dan Kematian Jurnalisme Barat
Gaza – 1miliarsantri.net : Pada 25 Agustus 2025, langit Khan Younis kembali dipenuhi dentuman ketika dua serangan udara beruntun menghantam Nasser Hospital—satu-satunya rumah sakit besar di selatan Gaza. Tragedi kemanusiaan dalam serangan pertama menewaskan warga sipil dan jurnalis, lalu serangan kedua atau double-tap strike mengenai tim penyelamat dan rekan media yang datang. Di antara korban tewas adalah Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Dagga (Associated Press), Mohammed Salama (Al Jazeera), Moaz Abu Taha (Reuters), dan Ahmed Abu Aziz (Middle East Eye), beberapa di antaranya meregang nyawa saat kamera mereka masih menyala, menyiarkan detik-detik terakhir hidup mereka. Seolah nyawa jurnalis di Gaza yang memberitakan kebenaran fakta tentang genosida yang berlangsung secara massif, dianggap sebagai ancaman serius bagi Israel. Peristiwa ini menambah daftar panjang jumlah jurnalis Palestina yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023, mencapai lebih dari 240 orang, angka yang menjadikan Gaza sebagai salah satu medan paling mematikan bagi wartawan dalam sejarah modern. (Reuters, 27/08/25). Namun di tengah gelombang duka itu, solidaritas global dari sesama jurnalis justru terasa nyaris sunyi, meninggalkan pertanyaan pahit yang terus menggema: ke mana suara kebebasan pers dunia ketika para wartawan Gaza menjadi sasaran, dan mengapa tidak ada gelombang solidaritas? “Saya Kehilangan Kata-Kata” Profesor studi media di Doha Institute for Graduate Studies, Mohamad ElMasry, mengaku tidak bisa lagi menyembunyikan rasa frustrasinya. “Israel telah berperang melawan jurnalisme sejak awal perang,” katanya kepada Al Jazeera. “Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka sangat terbuka tentang ini.” Yang lebih mengejutkannya adalah sikap komunitas global. “Pertanyaan saya: di mana para jurnalis internasional? Di mana The New York Times? Di mana CNN? Di mana media arus utama Barat? Ketika jurnalis Charlie Hebdo terbunuh pada 2015, itu memicu kemarahan global berbulan-bulan. Itu jadi berita utama di semua media Barat. Dan saya memuji mereka atas solidaritasnya. Tapi sekarang, di mana kemarahan itu?” Kekecewaan ElMasry mencerminkan jurang moral yang kian melebar: kematian jurnalis di Paris dihormati sebagai tragedi global, sementara kematian jurnalis di Gaza diperlakukan sebagai catatan kaki. Keheningan yang Mengiris Kontras ini sulit diabaikan. Tahun 2015, ribuan orang turun ke jalan di Eropa membawa slogan “Je suis Charlie.” Politisi, seniman, hingga kepala negara memberikan pernyataan solidaritas. Media Barat memimpin kampanye global membela kebebasan pers. Kini, ketika jumlah jurnalis Palestina yang terbunuh jauh lebih banyak, responsnya nyaris nihil. Tidak ada headline besar yang mendominasi halaman depan koran internasional selama berbulan-bulan. Tidak ada hashtag mendunia yang memobilisasi solidaritas publik. Tidak ada pawai besar yang menuntut perlindungan pers. Diamnya media Barat, bagi banyak pengamat, lebih menyakitkan daripada bom itu sendiri. Karena di balik diam itu, tersimpan pesan bahwa nyawa wartawan Palestina dianggap kurang berharga Impunitas yang Terus Berulang Lembaga seperti CPJ (Committee to Protect Journalists) dan Human Rights Watch mencatat pola lama: tentara Israel berkali-kali menarget wartawan, namun hampir tak pernah ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kasus Shireen Abu Akleh pada 2022 masih segar di ingatan—ditembak meski mengenakan rompi pers, dan sampai kini belum ada pelaku yang diadili. Impunitas ini memberi sinyal berbahaya: bahwa membungkam jurnalis Palestina tidak akan menimbulkan konsekuensi internasional. Dan selama media Barat memilih diam, pola ini akan terus berulang. Bias Narasi: Jurnalisme Kolonialis Mengapa newsroom besar begitu enggan bersuara? ElMasry menilai ini bukan sekadar kelalaian, melainkan konsekuensi dari bias naratif. Media Barat sering menggantungkan diri pada narasi resmi Israel, lalu mengulanginya tanpa verifikasi independen. Hasilnya, kematian wartawan Palestina direduksi sebagai “dampak sampingan” perang, bukan serangan sistematis terhadap kebebasan pers. Dalam istilah akademis, ini adalah bentuk jurnalisme kolonialis—di mana media global melanggengkan struktur kekuasaan kolonial: menentukan siapa yang pantas dianggap korban dan siapa yang suaranya bisa diabaikan. Orang Palestina direduksi menjadi statistik, bukan manusia dengan cerita. Padahal setiap wartawan yang gugur meninggalkan keluarga, kamera, dan kisah yang seharusnya menggugah hati dunia. Krisis Netralitas dan Profesionalisme Selama puluhan tahun, media Barat membangun citra sebagai pilar demokrasi, pembela kebenaran, dan suara moral global. Namun perang Gaza meruntuhkan klaim itu. Jika dua ratus lebih wartawan terbunuh tanpa memicu solidaritas global, apa arti netralitas yang selalu dikumandangkan? Jika newsroom besar takut bersuara lantang, lalu apa makna profesi ini selain sekadar bisnis berita? Krisis ini menyingkap bahwa yang mati di Gaza bukan hanya jurnalis Palestina, tetapi juga jiwa jurnalisme itu sendiri. Gaza sebagai Cermin Di Gaza, para jurnalis terus melaporkan meski tahu nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka bekerja dari reruntuhan, dari tenda pengungsian, bahkan dari rumah sakit yang dibombardir. Mereka mempertaruhkan hidup untuk memastikan dunia tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, jurnalis di Barat—yang bekerja dengan segala fasilitas dan keamanan—lebih sering memilih diam, atau berlindung di balik bahasa “netralitas” yang sebenarnya memihak status quo. Gaza akhirnya menjadi cermin pahit bagi jurnalisme global: memperlihatkan keberanian di satu sisi, dan ketakutan sekaligus kemunafikan di sisi lain. Sebuah Ajakan Mendesak Diam bukan lagi pilihan; diam berarti berkomplot dengan penindasan, bahkan mengkhianati profesi sendiri. Solidaritas seharusnya melintasi batas geopolitik, warna kulit, bahasa, atau paspor. Jika jurnalisme ingin tetap hidup sebagai profesi bermartabat, sebagai pilar demokrasi dan suara kebenaran, maka newsroom besar di Barat harus bangkit dari keheningan—menamai kebrutalan sebagai kebrutalan, menuntut perlindungan bagi rekan seprofesi di Gaza, dan mengembalikan martabat pers yang kini terancam terkubur bersama para wartawan Palestina yang gugur. Gaza telah memperlihatkan keberanian jurnalis lokal dalam kondisi mustahil; kini dunia menunggu, apakah rekan-rekan mereka di Barat siap berdiri, atau memilih membisu selamanya. (***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Foto : Reuters Sumber: Aljazeera https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/2/gaza-and-the-death-of-western-journalism https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/8/25/live-israel-intensifies-attacks-on-gaza-leaving-dozens-dead-in-a-day?update=3906499