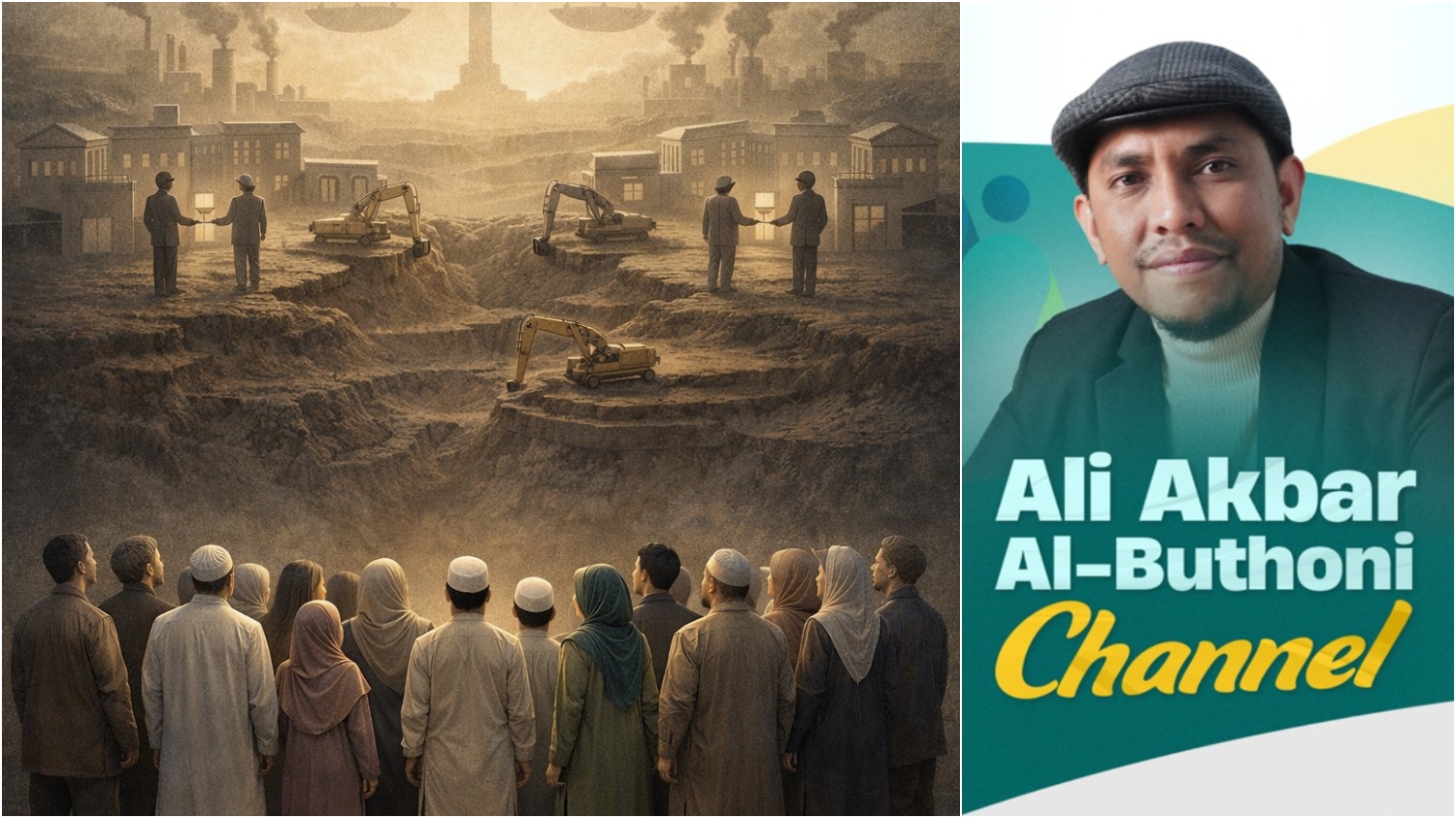Upaya Pembunuhan Delegasi Hamas Gagal, Gaza Kirim Pesan Ketabahan
Gaza – 1miliarsantri.net : Dari tenda-tenda pengungsian yang sesak di Khan Younis, di tengah reruntuhan yang menjadi saksi bisu kebiadaban perang, rakyat Gaza terus mengikuti setiap denyut berita dengan hati yang berdebar. Bukan hanya tentang nasib mereka sendiri, tetapi juga tentang mereka yang berbicara atas nama mereka di meja perundingan. Ketika kabar mengejutkan tentang upaya pembunuhan terhadap delegasi perunding Hamas di Doha merebak, kecemasan mendalam menyelimuti. Namun, ketika berita kegagalan upaya keji itu tiba, udara seolah dipenuhi dengan hela napas lega dan syukur yang tak terhingga. Ini bukan sekadar berita politik; ini adalah cerminan denyut nadi sebuah bangsa yang menolak untuk tunduk. Menurut laporan Tasnim News Agency pada Minggu 14 September, rudal yang ditembakkan oleh rezim Israel mengenai lima staf di Departemen Administrasi Hamas, termasuk Hammam, putra dari Wakil Kepala Biro Politik Hamas Khalil al-Hayyah, serta Badr al-Hamidi al-Dosari, seorang petugas keamanan Qatar. Keduanya gugur dalam serangan tersebut bersama tiga korban lainnya. “Rasa lega itu nyata, seakan beban berat terangkat dari pundak,” ujar seorang warga. Bagi mereka, delegasi ini bukan hanya politisi, melainkan bagian dari darah dan daging mereka sendiri, “bukan anak-anak kami, tetapi seperti anak-anak kami,” kata Um Mohammad dari Rafah dengan haru. Mereka adalah juru bicara yang berjuang demi nasib tawanan, demi menghentikan perang, dan demi masa depan Gaza yang hancur. Kegagalan upaya pembunuhan ini disambut dengan kegembiraan yang tulus, seolah-olah kemenangan kecil telah diraih di tengah badai penderitaan. Mereka adalah “kami” yang membela tanah air, membela darah, membela Palestina. Namun, di balik kegembiraan itu, ada pemahaman pahit yang mendalam: Israel tidak berniat mengakhiri perang ini. Seorang warga yang mengikuti berita yakin bahwa Israel akan menggunakan taktik semacam ini untuk menunda perundingan, bahkan menghancurkan Gaza sepenuhnya. Sejarah telah membuktikan, ketika para pemimpin seperti Sinwar dieliminasi, kebrutalan dan keganasan Israel justru meningkat. Ini bukan tentang Hamas semata; ini tentang kehancuran dan penghancuran identitas mereka sebagai bangsa. Namun, tekad rakyat Gaza tak goyah. Mereka telah bersabar dan akan terus bersabar. Upaya pembunuhan yang gagal ini, bagi mereka, adalah “kartu AS” yang kuat di tangan perlawanan dan negosiasi. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak akan bisa membungkam suara mereka, tidak peduli di mana pun mereka berada. “Kami sabar,” demikian pesan yang terus-menerus mengalir dari bibir mereka, “dan kalian juga harus terus sabar, sebagaimana kami mengenal kalian.” Mereka mendesak para negosiator untuk tetap teguh dan tidak menyerah pada pemerasan—baik dari Amerika, Israel, maupun pihak asing lainnya. Baca juga : Gaza yang Dijanjikan: Kota Pintar Bernilai Miliaran Dolar, Bentuk Penjajahan Wajah Baru Harapan mereka sederhana namun mendalam: “Semoga Allah meringankan penderitaan kami,” “Semoga Allah mengubah keadaan menjadi lebih baik,” dan “Semoga Allah menghilangkan kesedihan ini dari kami”. Mereka mendambakan kedamaian, persatuan, dan kebebasan. “Kami lelah, Palestina lelah,” kata Um Mohammad dengan suara bergetar. Ungkap Keterlibatan AS dalam Pendudukan Dikutip dari pusat informasi Palestina, Perwakilan Hamad di Teheran, Khaled Al-Qaddoumi, menegaskan bahwa upaya pembunuhan terhadap para pemimpin Hamas di Doha mengungkap keterlibatan langsung pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mendukung pendudukan Israel dan eskalasi kejahatan terhadap rakyat Palestina. Foto : Pusat Informasi Palestina Qaddoumi mengatakan bahwa AS terus mengabaikan komitmen dan janji-janjinya terkait proses gencatan senjata, seraya menciptakan ilusi bahwa mereka bersedia berneosiasi. Qaddoumi menambahkan bahwa serangan terbaru terjadi ketika para pemimpin sedang berkonsultasi di Doha untuk membahas apa yang disebut sebagai “Proposal Amerika.” Ia menuding serangan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Washington. Di tengah kehancuran besar-besaran, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, rakyat Gaza mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia: mereka akan tetap berdiri kokoh dan pantang menyerah. Tekad mereka adalah mengakhiri perang dan mencapai pembebasan penuh, atau menjadi syuhada. Ini adalah kisah tentang ketabahan jiwa, sebuah mercusuar harapan yang tak akan padam, meski api perang terus membakar tanah air mereka. Dari Khan Younis, dari setiap sudut Gaza, suara ketabahan ini bergema, menuntut keadilan dan kedamaian bagi sebuah bangsa yang tak pernah berhenti berjuang.(***) Penulis : Abdullah al-Mustofa Editor : Toto Budiman Sumber: Kanal YouTube Al Jazeera Mubasher, Pusat Informasi Palestina