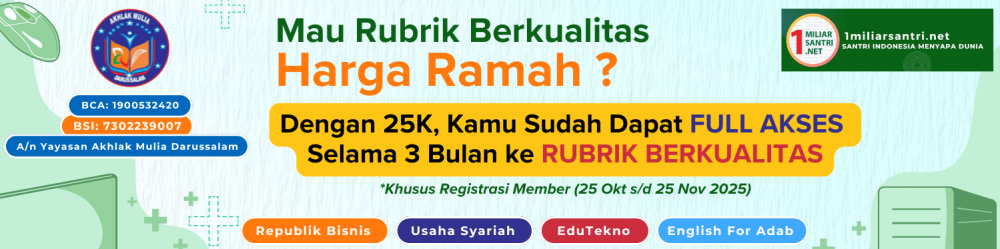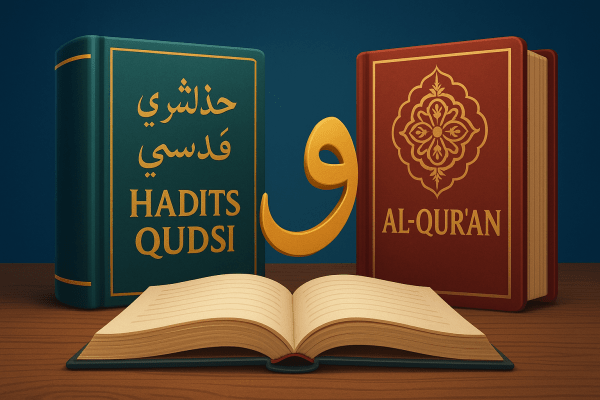Anak Sulit Konsentrasi? Berikut 7 Cara Mengatasi Gangguan Konsentrasi pada Anak
Bekasi – 1miliarsantri.net : Berbicara tentang konsentrasi, setiap manusia dalam aktivitasnya sangat membutuhkan konsentrasi agar suatu pekerjaan atau aktivitas dapat berjalan dengan baik. Konsentrasi yang dimaksud adalah pemusatan pemikiran atau perhatian kepada objek tertentu dengan mengesampingkan semua hal lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan objek tersebut. Salah satu aktivitas yang membutuhkan konsentrasi adalah belajar. Belajar merupakan proses memahami serta memusatkan pikiran terhadap bahan pelajaran yang sedang dipelajari. Dalam proses belajar, tidak sedikit orang tua atau guru yang mengeluhkan tentang anak didiknya yang mengalami gangguan konsentrasi saat belajar. Gangguan konsentrasi pada anak, biasanya dapat terlihat dari beberapa gejala, diantaranya adalah sebagai berikut : Gangguan konsentrasi pada anak seringkali disertai dengan gangguan lainnya seperti peningkatan gangguan emosi, agresif, gejala gerakan motorik berlebihan, hiperaktif serta gejala impulsif. Peningkatan gangguan emosi dan perilaku agresif yang terlihat berupa anak yang suka membanting barang, melempar atau berguling-guling dilantai. Sulit untuk bekerja sama, suka menantang, keras kepala bahkan suka menyakiti diri sendiri. Baca juga: Gebrakan Program MLB, Terpilih 1.000 Madrasah di Indonesia Mendapat Rp.25 Juta dari BAZNAS Lalu, bagaimana cara mengatasi gangguan konsentrasi pada anak? Gangguan konsetrasi pada anak tentunya membutuhkan penanganan khusus agar dapat meminimalisir gejala. Berikut 7 cara yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan konsesntrasi pada anak: Pertama, Penanganan secara khusus, dengan terapi nutrisi dan diet yaitu berupa keseimbangan diet karbohidrat, penanganan gangguan pencernaan, serta penanganan alergi makanan lainnya. Beberapa penelitian menyebutkan, setelah dilakukan eliminasi penyebab gangguan alergi makanan pada anak, ternyata didapatkan hasil peningkatan kemampuan konsentrasi anak. Kedua, Membangun Kerjasama yang efektif antara guru dan orang tua. Pada saat anak mengalami gangguan konsentrasi belajar, orang tua atau guru tidak perlu membentak, memarahi dan mengucilkan anak karena pada dasarnya anak juga mengalami kesulitan dalam mengendalikan gejolak yang meledak-ledak, baik berupa ucapan, perilaku atau gerakan. Oleh sebab itu, orang tua dan guru harus memiliki kesabaran yang ekstra dalam kasus ini. Ketiga, Memperlakukan anak secara hangat dan sabar namun konsisten dan tegas dalam menerapkan aturan dan tugas. Minta anak agar menatap mata saat berbicara, berikan arahan dengan nada yang lembut tanpa harus membentak. Keempat, Orang tua harus bisa mengenali bakat atau kecenderungan anak sejak dini sehingga orang tua dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi aktivitas anak dalam rangka menyalurkan kelebihan energinya tersebut. Misalnya, memasukkan anak pada klup sepakbola atau berenang agar anak dapat belajar bersosialisasi dan belajar untuk disiplin. Kelima, Bantu anak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi agar anak dapat mempelajari nilai-nilai yang dapat diterima dalam suatu kelompok. Keenam, Memberikan pujian dan penghargaan atas sikap dan perilaku anak yang dinilai berhasil melakukan sesuatu dengan benar. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Ketujuh, Konsisten dalam menerapkan aturan dan larangan agar anak memahami kenapa orang tua meminta anak untuk melakukan hal tersebut. Demikianlah cara yang dapat dilakukan dalam menangani gangguan konsentrasi pada anak. Semoga bermanfaat Penulis: Gita Rianti D Pratiwi Editor : Toto Budiman dan Iffah Faridatul Hasanah Sumber foto: Gemini AI Keywords: Gangguan konsentrasi, Anak, Cara Menangani Gangguan Konsentrasi pada Anak Sumber : Ulfa, Maria. 2015. Beragam Gangguan Paling Sering Menyerang Anak. Yogyakarta : FlashBooks