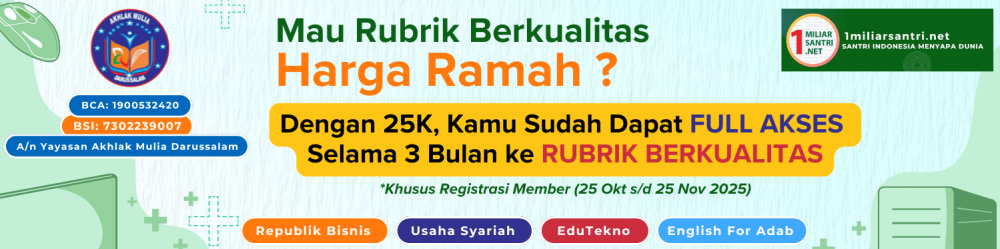Jumat Hari yang Istimewa Bagi Umat Islam — Keberkahan dan Keistimewaan yang Sering Kita Lupakan
Hari Jumat bukan sekadar hari biasa. Inilah hari penuh keberkahan dan ampunan bagi umat Islam. Bekasi – 1miliarsantri.net: Hari Jumat merupakan hari paling istimewa bagi umat Islam. Temukan berbagai keutamaan dan amalan yang dianjurkan pada hari Jumat agar hidup penuh berkah dan pahala. Jumat adalah hari yang istimewa dan penuh berkah jika umat Islam memahami keutamaan hari Jumat, apa saja amalan sunah yang dianjurkan Rasulullah, dan telah diikuti oleh para sahabatnya, para tabi’in hingga masa kita saat ini. Berikut rangkuman keistimewaan hari Jumat yang disajikan dalam rubrik Khazanah, dan insya Allah menjadi salah satu referensi dan literasi bagi umat Islam dalam rangka muhasabah diri. Sholawat di Hari Jumat dan Keistimewaannya Hari Jumat merupakan hari penuh rahmat dan ampunan, di mana amal ibadah dilipatgandakan pahalanya.Membaca sholawat di hari ini bukan hanya bentuk cinta kepada Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku.”(HR. Tirmidzi) Hari yang Diciptakan dengan Penuh Kemuliaan Tahukah kamu, hari Jumat disebut sebagai sayyidul ayyam — penghulu segala hari?Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat.” (HR. Muslim) Pada hari inilah Allah menciptakan Nabi Adam AS, memasukkannya ke surga, dan mengeluarkannya darinya. Bahkan, kelak kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Maka tidak heran jika Jumat menjadi hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wata’ala. Waktu Berdoa yang Paling Mustajab Ada satu waktu di hari Jumat yang sangat dinantikan para mukmin — waktu mustajab, di mana doa tidak akan ditolak. Banyak ulama berpendapat waktu itu berada antara ashar hingga magrib. Bayangkan, hanya dengan memperbanyak doa di penghujung Jumat, kita bisa mendapatkan peluang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Cahaya di Antara Dua Jumat: Surah Al-Kahfi Setiap Jumat, umat Islam dianjurkan membaca Surah Al-Kahfi.Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Barang siapa membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar cahaya di antara dua Jumat.” (HR. Al-Hakim) Surah ini bukan hanya membawa cahaya dan ketenangan, tetapi juga perlindungan dari fitnah dunia, termasuk fitnah Dajjal. Cukup 20 menit membacanya — namun pahalanya mengalir sepanjang pekan. Shalat Jumat: Lebih dari Sekadar Kewajiban Shalat Jumat bukan hanya menggugurkan kewajiban mingguan bagi laki-laki Muslim, tapi juga simbol persaudaraan umat Islam.Dalam khutbah Jumat, kita diingatkan untuk kembali ke jalan kebenaran, memperbarui niat, dan memperbaiki amal. Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam memperingatkan: “Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat Jumat tanpa uzur, maka Allah akan menutup hatinya.” (HR. Abu Dawud) Jumat: Waktu Penghapus Dosa Hari Jumat menjadi momentum luar biasa untuk pengampunan dosa. “Shalat lima waktu, dari Jumat ke Jumat, menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi.” (HR. Muslim) Setiap Jumat datang, Allah memberi kesempatan untuk memulai lembaran baru — penuh rahmat dan ampunan. Hari Terbaik untuk Sedekah dan Amal Baik Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak sedekah di hari Jumat, karena pahalanya dilipatgandakan. Banyak umat Islam pada hari Jumat bersedekah dalam bentuk makanan dan minuman yang dibagikan di masji-masjid dan di berbagai tempat yang baik untuk membantu sesama. Waktu untuk Merenung dan Memperbaiki Diri Jumat bukan hanya hari beramal, tapi juga hari untuk muhasabah diri.Renungkan perjalanan hidup, perbanyak istighfar, dan siapkan hati untuk menjadi lebih baik di pekan berikutnya. Jadikan Jumat Sebagai Momentum Spiritual Hari Jumat adalah anugerah.Setiap langkah menuju masjid, setiap doa yang terucap, dan setiap ayat yang dibaca membawa keberkahan tersendiri. Mari jadikan Jumat bukan hanya rutinitas mingguan, tapi momen penyucian jiwa dan pengingat akan kasih sayang Allah Subhanahu Wata’ala. “Perbanyaklah shalawat di hari Jumat, karena shalawat kalian akan disampaikan langsung kepadaku.” — (HR. Abu Dawud) Semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa merahmati dan memberkati umat Islam di segenap penjuru bumi. Umat yang senantiasa menjaga ketaatan dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan saling nasihat-menasihati untuk kebaikan dan ketakwaan.*** Penulis : Thamrin Humris Editor : Thamrin Humris Foto Koleksi Pribadi dan iluistrasi istimewa