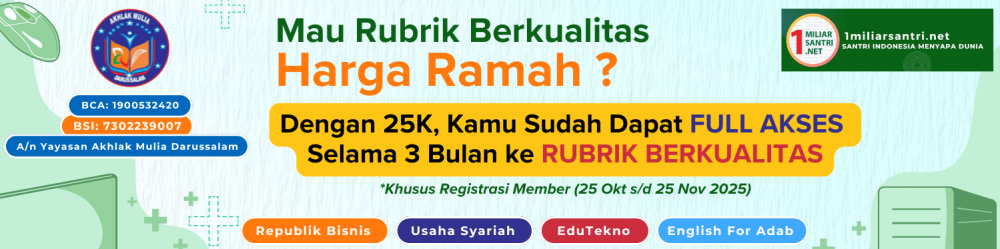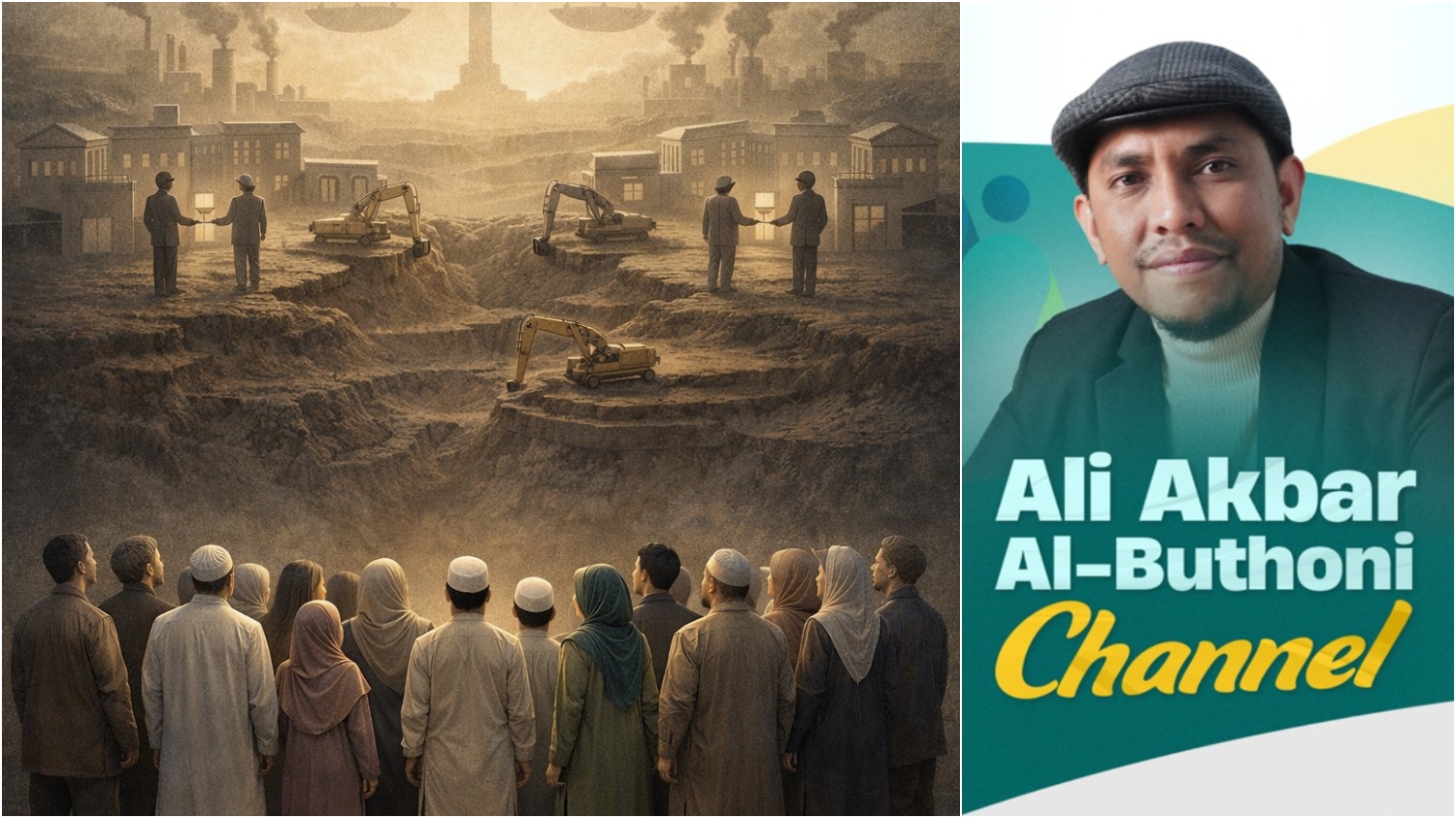Pesantren Tremas Pacitan, antara Sejarah dan Keunikan nya

Pacitan – 1miliarsantri.net : Meski letaknya yang berada di pelosok selatan Jawa, nama Pondok Tremas Pacitan cukup masyhur hingga ke penjuru dunia. Pesantren ini telah melahirkan banyak ulama yang tidak sekadar jago kandang di Jawa saja, tapi juga berhasil tandang unjuk gigi hingga ke Malaysia, Thailand, Al-Azhar Mesir hingga ke Mekah. Tidak hanya ulama hebat yang lahir dari Pondok Tremas, namun juga warisan keilmuan yang menjadi jejaring rantai intelektual ulama Nusantara.
Sejarah Perguruan Islam Pondok Tremas tidak bisa lepas dari KH Abdul Mannan (1830-1862) sebagai pendiri. Pemilik nama kecil Raden Bagus Darso itu merupakan putra R. Ngabehi Dipomenggolo, seorang Demang di daerah Semanten pinggiran Kota Pacitan, Jawa Timur.
Sejak kecil KH Abdul Manan dikenal cerdas dan tertarik pada problematika religius. Saat memasuki usia remaja, dikirim ke Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo untuk mendalami ilmu agama Islam di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari. Ia terkenal sebagai santri yang cerdas, rajin, dan tekun dalam belajar. Tak heran ia menjelma sebagai santri teladan.
Saat KH Abdul Mannan selesai menimba ilmu di Tegalsari, ia pulang ke Semanten. Ia menyelenggarakan pengajian dengan sangat sederhana. Warga Pacitan menyambut baik keberadaan majelis tersebut. Bermula dari situ, ia mendirikan pondok di sekitar masjid untuk para santri yang datang dari jauh.
Namun beberapa waktu kemudian, pondok tersebut pindah ke daerah Tremas setelah KH Abdul Mannan menikah dengan Putri Demang Tremas R. Ngabehi Honggowijoyo. R. Ngabehi Honggowijoyo sebenarnya kakak kandung R. Ngabehi Dipomenggolo.
Di antara penyebab pondok itu dipindahkan adalah pertimbangan kekeluargaan yang dianggap lebih baik jika pinda ke daerah Tremas. Mertua dan istri beliau menyediakan lokasi yang jauh dari keramaian atau pusat pemerintahan. Daerah itu dinilai kondusif bagi santri yang hendak memperdalam ilmu agama.
Berbekal lokasi tersebut, KH Abdul Mannan mendirikan pondok pesantren yang kemudian dikenal ‘Pondok Tremas’ sekitar 1830 M.
Selain menjadi salah satu santri terbaik KH Hasan Besari, KH Abdul Mannan termasuk ke dalam generasi pertama orang Indonesia di Al-Azhar Mesir. Dalam buku Jauh di Mata Dekat di Hati; Potret Hubungan Indonesia-Mesir terbitan KBRI Kairo disebutkan, KH Abdul Mannan merupakan salah satu pelajar pertama Indonesia yang tinggal di Mesir pada 1850-an. Itu ditandai dengan komunitas orang Indonesia yang dijumpai di komplek Masjid Al-Azhar. Ini diperkuat dengan adanya Ruwak Jawi (hunian bagi orang Indonesia) di masjid itu.
Beliau tinggal di Mesir sekitar 1850-an. Dia berguru kepada Grand Syeikh ke-19, Ibrahim Al Bajuri. Jadi wajar di tahun-tahun itu ditemukan kitab Fath al-Mubin, syarah dari kitab Umm al-Barahin yang merupakan kitab karangan Grand Syeikh Ibrahim Bajuri mulai dibaca di beberapa pesantren di Indonesia.
Pengembaraan KH Abdul Mannan itu diikuti generasi selanjutnya seperti KH Abdullah (Putra KH Abdul Manan Dipomenggolo), tiga kakak beradik Syaikh Mahfudz Attarmasi, KH Dimyathi Tremas, KH Dahlan Al Falaki Tremas, lalu putra KH Abdullah yang menuntut ilmu di Makkah.
KH Abdul Manan berhasil meletakkan batu landasan sebagai pangkal berpijak ke arah kemajuan dan kebesaran, serta keharuman pondok pesantren di Nusantara. Selain itu, kegigihan dalam mendidik anaknya menjadi ulama terbilang sukses. Putra beliau menjadi ulama yang tak hanya menguasai kitab klasik, namun mampu menyusun berbagai macam kitab dengan kontribusi yang sangat besar di Indonesia seperti Syaikh Mahfudz, seorang ulama besar Nusantara yang dijadikan rujukan hingga Malaysia dan Thailand. Ia juga pernah menjadi Imam Masjidil Haram dan pemegang sanad Shahih Bukhari-Muslim.
Maka tak berlebihan jika KH Abdul Manan disebut sebagai pelajar Indonesia pertama di Al-Azhar sekaligus peretas jejaring intelektual generasi ulama-ulama nusantara. Dalam kitab Al-Ulama’ Al-Mujaddidun karya KH Maimoen Zubair Sarang Rembang, KH Abdul Manan merupakan sosok yang pertama kali membawa, mengaji, dan mempopulerkan kitab Ithaf Sadat Al-Muttaqin, yaitu syarah dari kitab Ihya’ Ulumuddin karya Imam al-Ghazali.
Sepeninggal KH Abdul Mannan, Pondok Tremas diwarisi oleh putra-putra beliau yakni KH Abdullah (1862-1894), KH Dimyathie (1894-1934), dan Habib Dimyathi (1948-1997) & periode KH Haris Dimyathi (1948-1994). Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh KH Fuad Habib Dimyathi dan KH Luqman Haris Dimyathi.
Hari ini, Pondok Pesantren Tremas Pacitan dalam pengembangan pendidikannya membuka beberapa unit pendidikan sebagai berikut TK Al Tarmasi jenjang 2 tahun, TPQ-Madin Al Tarmasi Jenjang 3 Tahun, Madrasah Salafiyah Tsanawiyah Jenjang 3 Tahun, MTs Pondok Tremas Jenjang 3 tahun, Madrasah Salafiyah Mu’adalah, Jenjang 3 tahun, Lembaga Vokasional Jenjang 1 Tahun, Ma’had Aly Al Tarmasi Jenjang 4 tahun, dan Tahfidzul Qur’an.
Pondok Tremas juga memiliki ekstrakurikuler yakni tahsin dan tahfidz, takhassus kitab salaf, seni baca Al-Qur’an, khitobah 3 bahasa, hadroh, praktek ubudiyah, pramuka, beladiri, english club, komputer dan berbagai kegiatan olahraga seperti futsal, volley, basket, dan tenis meja.
Selain itu, Pondok Tremas juga memiliki metode pengajaran klasik yakni pengajian weton dan pengajian sorogan. Dua metode ini marak ditemui di pesantren-pesantren salafiyah.
Pertama yaitu pengajian wetonan merupakan salah satu sistem pendidikan di pondok tremas yang asli atau tradisional. Seorang kiai membacakan teks kitab tertentu sekaligus terjemahannya. Kemudian para santri (terdiri dari berbagai tingkatan) menyimak, mencatat, atau mengartikan hal-hal yang belum dimengerti dari arti kalimat yang dibacakan.
Sistem ini bersifat bebas, karena tidak absensi santri. Santri boleh datang, boleh tidak. Semua santri pun digabung, jadi tidak ada kenaikan kelas. Maka itu santri yang aktif bisa menamatkan kitab lebih cepat dan lanjut ke kitab lain.
Kedua, pengajian Sorogan yang merupakan sistem tradisional yang diselenggarakan secara sendiri (Individu, yaitu seorang santri satu persatu secara bergantian menghadap ustadz atau kyai yang akan membacakan kitab-kitab dan menerjemahkannya kedalam bahasa Jawa).
Para santri kemudian diminta mengulangi dan menerjemahkan kitab kata demi kata seperti yang dibacakan oleh sang guru. Penerjemahan tersebut dapat dibuat sedemikian rupa dengan tujuan agar santri dapat belajar tata bahasa secara langsung di samping mengetahui arti kitab-kitab itu.
Pondok pesantren memiliki beberapa tradisi unik bagi santri baru. Pertama, Tidak Tidur Siang Selama Satu Minggu. Satu pekan pertama santri baru Pondok Tremas akan menjalani tradisi unik yang sudah mengakar yakni tradisi tidak tidur siang selama tujuh hari sejak hari pertama kedatangan mereka di Tremas. Tidak tidur siang, suatu hal yang kelihatannya sepele dan ringan ini ternyata sangat sulit dilakukan. Dalam praktIknya, biasanya para santri baru selalu mendapat berbagai cobaan dan godaan, seperti merasakan kantuk yang sangat berat.
Kedua, Ziarah 41 hari tanpa putus. Tradisi ini sudah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Setiap santri baru “diusahakan”, bahkan ada yang “wajib” untuk rutin berziarah ke makam masyayikh (sesepuh) Pesantren selama 41 hari berturut-turut tanpa putus.
Ketiga, Nahun atau tidak pulang selama 3 tahun 3 bulan. Nahun, disebut juga tirakat atau lelakon. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh santri KH Dimyati (Wafat 1934 M). Saat itu, Pondok Pesantren berkembang sangat pesat. Banyak santri dari berbagai penjuru nusantara bahkan dari negara tetangga datang untuk menuntut ilmu.
Nahun menjadi tradisi karena letak pesantren jauh dari kampung halaman para santri. Sementara waktu itu, alat transportasi belum ada sama sekali, kecuali gerobak dan sejenisnya. Maka muncullah tradisi “Nahun” dalam arti hakiki yaitu tekun belajar dan tidak keluar dari komplek pesantren dalam jangka waktu 3 tahun ataupun 3 bulan dan 3 hari. (gus)
Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.