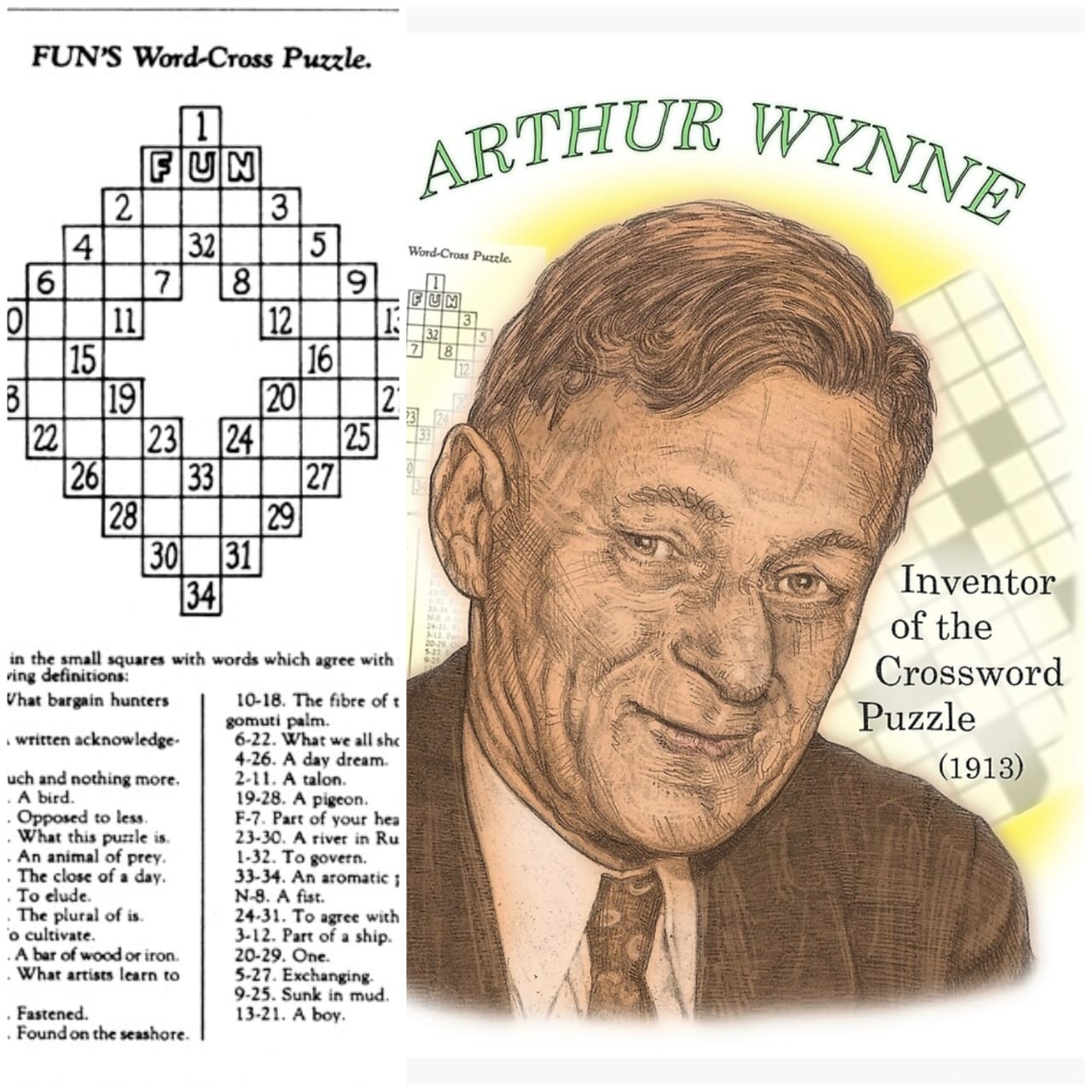Kisah Perjalanan Haji Masa Lampau

Jakarta – 1miliarsantri.net : Berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan keinginan setia Muslim seluruh penjuru dunia, termasuk umat Islam di Indonesia. Sejak berabad-abad silam hingga kini, jamaah asal Indonesia selalu menempati porsi terbesar di setiap penyelenggaraan haji dan Umrah nya.
Tentu saja, menunaikan rukun Islam kelima pada masa kini berbeda dengan masa terdahulu. Saat ini, orang-orang memiliki opsi transportasi yang lebih efisien yakni menggunakan moda angkutan pesawat terbang. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya, jalur laut merupakan satu-satunya pilihan yang ada.
Seperti hal nya yang pernah dialami KH Abdussamad, seorang jamaah asal Kalimantan Selatan yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1948. Dia menuturkan jamaah haji Indoneasia yang lebih dikenal dengan Nusantara pada zaman dahulu menghadapi pelbagai aral rintangan yang ditemui, baik menjelang keberangkatan maupun dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Bahkan, kebanyakan dari jamaah masih saja menjumpai kendala-kendala begitu berada di Tanah Suci.
Pelayaran dari Nusantara ke Jazirah Arab sejak abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20 Masehi tidak bisa dikatakan aman seluruhnya—atau tidak sebaik masa kini. Durasi perjalanan via laut itu mencapai kira-kira enam bulan. Selama menumpangi kapal laut, jamaah haji mesti menghadapi kenyataan yang tidak semua menyenangkan.
“Sering kali kapal berkondisi buruk. Terlebih lagi, masih banyak jamaah haji pada masa itu yang memilih kapal barang (kargo), alih-alih kapal yang memang khusus untuk penumpang. Dalam kapal kargo, jamaah diberi tempat dalam ruang gudang (palka), masing-masing seluas satu hingga satu setengah meter persegi,” ungkapnya.
Kiai Abdussamad menambahkan, banyak jamaah hanya mendapatkan ruang seluas 60 x 100 cm persegi. Itu pun masih ada sekira 150 orang jamaah yang tidak dapat tempat di atas kapal. Bayangkan, selama enam bulan pelayaran mereka mesti bertahan di ruangan sesempit itu—atau bahkan tak kebagian tempat sama sekali. Belum lagi urusan tidur, mandi, buang air, dan memasak makanan. Kondisi demikian masih menjadi pemandangan umum hingga era 1950-an.
Bukan hanya soal fasilitas, perjalanan pun dirundung bahaya dari luar. Jamaah masih menghadapi potensi kapal karam atau diserang kawanan perompak. Suatu kasus terjadi pada 1893, yakni kapal Samoa yang dikontrak firma Herkloys dan membawa sebanyak 3.600 jamaah haji. Muatan itu jauh melebihi kapasitas kapal. Ketika badai menerjang, porak-porandalah segala barang di atas kapal itu. Korban jiwa mencapai 100 orang.
Terdapat naskah yang disimpan keluarga Muhammad Said dari Mindanao, Filipina, memuat teks bertajuk “Alkisah tatkala Tuan Muhammad Said Berlayar dari Negeri Hudaidah.”
Di dalamnya, tercatat kesaksian bahwa pada 1803 kapal yang ditumpangi Tuan Muhammad Said dan rombongan asal Mindanao karam ketika sampai di titik antara Hudaidah dan Makkah. Bagaimanapun, jamaah tersebut akhirnya sampai ke Tanah Suci sekira satu bulan berikutnya.
Persebaran penyakit menular juga mengkhawatirkan jamaah haji. Wabah yang sering terjadi dan menelan ribuan korban, antara lain, adalah kolera. Pada 1865, sebanyak 15 ribu orang meninggal dunia akibat terjangkit kolera di Hijaz. Epidemi itu lalu dengan cepat menyebar hingga ke negeri-negeri tetangga Arab. Di Mesir, tercatat 60 ribu orang wafat akibat sakit tersebut.
Van Dijk (1997) mengutip disertasi dr Abdoel Patah yang bertajuk “Aspek Kesehatan Perjalanan Haji ke Makkah.” Dalam karya ilmiah yang terbit pada 1935 itu, terungkap bahwa selama era 1920-an, ada sekitar 10 persen jamaah haji meninggal di Tanah Suci atau dalam perjalanan.
Suaka karantina dibangun pertama kalinya pada 1831 di Pulau Abu Sa’ad, dekat Terusan Suez. Sekitar 50 tahun kemudian, sarana itu ditutup. Penggantinya didirikan di Pulau Kamaran, sebelah selatan Jeddah.
Mulai tahun 1903, karantina dikelola bersama oleh Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan tiga negara Eropa Barat, yakni Britania Raya, Prancis, dan Belanda. Kerja sama ini mewujud dalam Internationale Gezondheidsraad yang bermarkas di Iskandariah, Mesir.
Usai pelayaran yang melelahkan, jamaah tetap mesti bersabar. Menjejakkan kaki di Jazirah Arab pada masa itu berarti menghadapi beberapa tantangan lainnya. Di antaranya adalah potensi penjarahan dan pemerasan.
Pada abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20 M, orang-orang Arab Badui umumnya menguasai kawasan gurun pasir antara Jeddah, Makkah dan Madinah. Bahkan, pemerintahan yang sah—baik sultan Turki Utsmaniyah maupun syarif Makkah—setidaknya hingga 1920-an tidak mampu mengamankan area tersebut. Maka, tidak jarang jamaah haji dirintangi kelompok Badui.
Karena merasa sebagai pemilik wilayah, para Badui itu meminta semacam pajak atau “uang lewat” kepada jamaah haji yang melintas. Malahan, tidak jarang pula mereka menjarah kafilah-kafilah yang lewat.
Jamaah asal Indonesia menjadi incaran favorit karena hampir pasti membawa bekal uang yang lebih banyak daripada yang lain. Pada 1924, RAA Wiranatakusumah mencatat, rombongan hajinya urung ke Madinah karena merasa, perjalanan dari Makkah ke sana terlalu berbahaya.
Adapun pemerasan telah menjadi soal yang memusingkan jamaah haji bahkan sejak ratusan tahun sebelum era modern. Pada abad ke-12 M, Ibnu Jubayr mencatat dengan geram bahwa orang Hijaz “menganggap layak” mengeksploitasi semua orang asing, termasuk mereka yang sedang melaksanakan perjalanan haji.
“Karena mereka menganggap jamaah sebagai salah satu sumber nafkah utama buat mereka, maka mereka merampas segala hartanya, dan senantiasa mempunyai alasan untuk mengambil segala miliknya (jamaah),” tulis Ibnu Jubayr.
Kesaksian mengenai pemerasan diungkapkan baik oleh orang Indonesia sendiri maupun pengamat Belanda. Pelaku tindakan buruk itu adalah orang-orang Arab, baik yang berperan (resmi) sebagai mutaqif maupun pedagang—lebih-lebih Arab Badui. Mereka menganggap rendah jamaah dari negeri-negeri yang jauh, termasuk Indonesia.
Jamaah haji dari Nusantara dinamakan, secara maknawi netral, sebagai Jawi, yakni merujuk pulau tempat kebanyakan mereka berasal. Namun, orang-orang Jawi disebut penduduk Arab dengan julukan yang peyoratif pula. Misalnya, farukha (jamak kata farkh, ‘ayam itik’) dan baqar, ‘hewan ternak.’ Demikian dicatat Snouck Hurgronje (1931).
Buya Hamka mencatat kesannya: “Setiap jamaah itu (asal Indonesia –Red) tak ubahnya dengan kambing-kambing (di mata penduduk).” Pemerasan yang menimpa mereka menjadikan orang-orang Melayu dan Jawa “di mata orang Arab … adalah ‘sapi perah’”, demikian tulis Abdul Majid.
Hurgronje (1931) juga mencatat bagaimana modus orang-orang Arab memeras jamaah haji Indonesia kala itu. Mereka memanfaatkan keluguan atau ketidaktahuan jamaah. Orang-orang yang hendak menunaikan ziarah ke Baitullah itu disuruhnya melakukan macam-macam kunjungan ke tempat-tempat tertentu.
“Perjalanan ini mahal dan melelahkan karena di luar agenda haji sesungguhnya. Orang-orang itu ikut saja arahan karena tidak mengetahui rukun-rukun dan sunah-sunah ibadah haji,” tutup Kiai Abdussamad. (fq)
Eksplorasi konten lain dari 1miliarsantri.net
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.